Jejak Pulau Pagama
Oleh: Mohtar Umasugi
(Dosen STAI Babusalam Sula)
Dari atas KM Ukiraya, mata saya tertuju pada hamparan laut biru yang membentang di antara Sanana dan Mangoli. Di kejauhan, saya mencari sosok kecil yang dulu begitu akrab bagi para pelaut. Pulau itu dahulu menjadi tempat singgah bagi siapa pun yang melintasi jalur ini. Di sanalah para nelayan menunggu badai reda, menyalakan api, dan beristirahat sejenak sebelum kembali menantang ombak.
Namun kini, Pulau Pagama telah hilang ditelan abrasi pantai. Yang tersisa hanyalah permukaan laut yang datar dan tenang, seolah menyimpan kisah yang tak sempat diceritakan. Laut seakan menelan bagian dari sejarah kita, tanpa suara, tanpa jejak.
Saat kapal terus melaju, saya termenung lama. Hilangnya Pagama bukan sekadar cerita tentang abrasi, melainkan simbol tentang kehilangan yang lebih dalam—kehilangan kesadaran ekologis, kehilangan keseimbangan antara manusia dan alam, serta kehilangan makna atas sesuatu yang dulu begitu dekat dengan kehidupan.
Dalam perspektif filsafat, kita baru menyadari nilai sesuatu ketika ia telah tiada. Martin Heidegger menyebutnya sebagai momen ketika keberadaan menyingkap dirinya melalui ketiadaan. Maka, ketika Pagama hilang, justru di situlah ia “hadir” secara paling kuat dalam kesadaran kita. Ia menjadi cermin tentang betapa rapuhnya hubungan manusia dengan alam yang sering diabaikan.
Saya teringat, dulu para pelaut sering menjadikan Pagama sebagai tanda arah dan tempat singgah. Kini, laut di sekitarnya menjadi sunyi dan asing. Dan mungkin di situlah pelajarannya: bahwa alam yang kita abaikan perlahan akan pergi, sebagaimana Pulau Pagama yang kini hanya hidup dalam ingatan.
Pulau Pagama yang hilang seperti metafora dari kondisi manusia modern—yang perlahan kehilangan akar, kehilangan tempat berpijak di tengah arus perubahan. Kita terlalu sibuk bergerak hingga lupa untuk berhenti sejenak, menatap ke belakang, dan merenungi apa yang telah hilang di sepanjang jalan.
Di sinilah laut berbicara dengan caranya sendiri. Ia tidak berteriak, tetapi memberi isyarat. Ia mengingatkan bahwa setiap abrasi bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga tanda bahwa ada yang salah dengan cara kita menjaga kehidupan.
Ketika pagi mulai merekah, dan cahaya matahari perlahan memantul di permukaan laut yang kini menelan Pagama, saya menatap lama ke arah di mana pulau itu dulu berdiri. Udara terasa segar, namun ada hening yang menyesak. Di atas dek, dengan tangan menggenggam pena dan kertas, saya menulis catatan kecil ini:
“Tak ada yang benar-benar hilang jika kita mau mengingatnya dengan makna. Tapi tak ada pula yang bisa bertahan jika kita berhenti menjaga.”
Pulau Pagama telah tiada, tetapi ia meninggalkan pesan bagi kita semua—bahwa setiap kehilangan adalah panggilan untuk bertanggung jawab, agar kita tidak kembali kehilangan hal-hal lain yang tak tergantikan: alam, nilai, dan kemanusiaan kita sendiri.
Kisah hilangnya Pulau Pagama adalah potret kecil dari wajah besar persoalan ekologis yang kini kita hadapi. Ia bukan hanya soal abrasi, tetapi juga tentang cara kita memperlakukan bumi—tentang kesadaran yang memudar di antara kepentingan pembangunan dan abainya kebijakan. Dari atas KM Ukiraya, saya belajar bahwa laut bukan sekadar bentangan air, melainkan ruang renung yang menegur kita dengan lembut.
Jika kita tidak belajar dari hilangnya Pagama, maka bukan mustahil suatu hari nanti kita juga akan kehilangan lebih banyak: daratan, sejarah, bahkan masa depan.
Tulisan ini saya buat di pagi hari di atas KM Ukiraya ketika melintasi bekas pulau pagama dari Ternate menuju Sanana.***






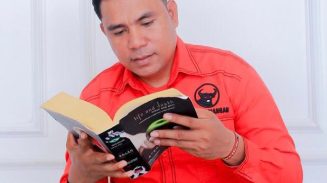
















Tinggalkan Balasan